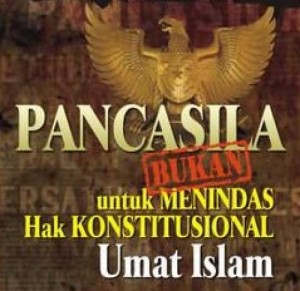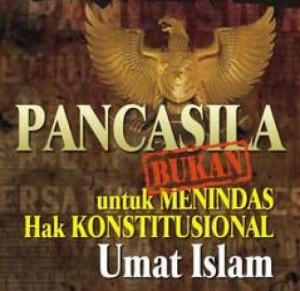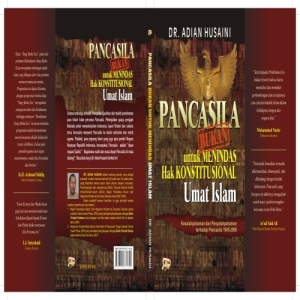Jas Merah: Pancasila Bukan Untuk Menindas Hak Konstitusional Umat Islam
HARIAN Republika, Rabu (11/5/2011) menurunkan berita berjudul: “Kembalikan Pancasila dalam Kurikulum”. Berita itu mengungkap pernyataan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie yang mempertanyakan mengapa Pendidikan Pancasila hilang di kurikulum pendidikan. Kata Aburizal, Pancasila tidak boleh dikerdilkan dengan hanya menjadi bagian dari pendidikan kewarganegaraan.
“Sikap Partai Golkar jelas, kembalikan materi pendidikan Pancasila menjadi bagian dari kurikulum pendidikan secara khusus, karena materinya harus diajarkan secara tersendiri,” kata Aburizal Bakrie.
Menurut Aburizal Bakrie, penghapusan pendidikan Pancasila adalah sebuah upaya memotong anak bangsa ini dari akar budayanya sendiri. Pancasila adalah pintu gerbang masuk pelajaran tentang semangat nasionalisme, gotong royong, budi pekerti, nilai-nilai kemanusiaan, kerukunan, dan toleransi beragama.
Demikian seruan Partai Golkar tentang Pancasila sebagaimana disampaikan oleh Ketua Umumnya. Akhir-akhir ini kita sering mendengar seruan berbagai pihak tentang Pancasila. Tentu saja, ini bukan hal baru. Berbagai seminar, diskusi, dan konferensi telah digelar untuk mengangkat kembali “nasib Pancasila” yang terpuruk, bersama dengan berakhirnya rezim Orde Baru, yang sangat rajin mengucapkan Pancasila.
Partai Golkar atau siapa pun yang menginginkan diterapkannya di Pancasila, seyogyanya bersedia belajar dari sejarah; bagaimana Pancasila dijadikan sebagai slogan di masa Orde Lama dan Orde Baru, dan kemudian berakhir dengan tragis. Sejak tahun 1945, Pancasila telah diletakkan dalam perspektif sekular, yang lepas dari perspektif pandangan alam Islam (Islamic worldview). Padahal, sejak kelahirannya, Pancasila – yang merupakan bagian dari Pembukaan UUD 1945 – sangat kental dengan nuansa Islamic worldview.
Contoh terkenal dari tafsir sekular Pancasila, misalnya, dilakukan oleh konsep Ali Moertopo, ketua kehormatan CSIS yang sempat berpengaruh besar dalam penataan kebijakan politik dan ideologi di masa-masa awal Orde Baru. Mayjen TNI (Purn) Ali Moertopo yang pernah menjadi asisten khusus Presiden Soeharto merumuskan Pancasila sebagai “Ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Tentang Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, misalnya, Ali Moertopo merumuskan, bahwa diantara makna sila pertama Pancasila adalah hak untuk pindah agama. “Bagi para warganegara hak untuk memilih, memeluk atau pindah agama adalah hak yang paling asasi, dan hak ini tidak diberikan oleh negara, maka dari itu negara RI tidak mewajibkan atau memaksakan atau melarang siapa saja untuk memilih, memeluk atau pindah agama apa saja.”
Tokoh Katolik di era Orde Lama dan Orde Baru, Pater Beek S.J., juga merumuskan makna sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai konsep yang netral agama, dan tidak condong pada satu agama. Ia menggariskan tentang masalah ini:
“Barang siapa beranggapan Sila Ketuhanan ini juga meliputi anggapan bahwa Tuhan itu tidak ada, atheisme (materialisme); atau bahwa Tuhan berjumlah banyak (politeisme), maka ia tidak lagi berdiri di atas Pancasila. Pun pula jika orang beranggapan bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa itu hanya tepat bagi kepercayaan Islam atau Yahudi saja, misalnya, maka orang semacam itu pada hakikatnya juga tidak lagi berdiri di atas Pancasila.” (J.B. Soedarmanta, Pater Beek S.J., Larut tetapi Tidak Hanyut).
Tetapi, sebagian kalangan ada juga yang memahami, bahwa sila Ketuhanan Yang Maha Esa juga menjamin orang untuk tidak beragama. Drs. R.M. S.S. Mardanus S.Hn., dalam bukunya,“Pendidikan—Pembinaan Djiwa Pantja Sila”, (1968), menulis: “Begitu pula kita harus mengetahui, bahwa orang yang ber-Tuhan tidak sekaligus harus menganut suatu agama. Bisa saja orang itu ber-Tuhan, yaitu percaya dan menyembah Tuhan Yang Maha Esa, tetapi tidak memeluk suatu agama, karena ia merasa tidak cocok dengan ajaran-ajaran dan dogma-dogma agama tertentu. Orang yang ber-Tuhan tetapi tidak beragama bukanlah seorang ateis. Pengertian ini sebaiknya jangan dikaburkan.”
Pastor J.O.H. Padmaseputra, dalam bukunya, “Ketuhanan di Indonesia” (Semarang, 1968), menulis: “Apakah orang yang tidak beragama harus dipandang ateis? Tidak. Karena amat mungkin dan memang ada orang tidak sedikit yang percaya akan Tuhan, tetapi tidak menganut agama yang tertentu.” (Dikutip dari buku Pantjasila dan Agama Konfusius karya RimbaDjohar, (Semarang: Indonezia Esperanto-Instituto, MCMLXIX), hal. 34-35).
Padahal, jika dicermati dengan jujur, rumusan sila Ketuhanan Yang Maha Esa ada kaitannya dengan pencoretan tujuh kata dalam Piagam Jakarta: Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Bung Hatta yang aktif melobi tokoh-tokoh Islam agar rela menerima pencoretan tujuh kata itu, menjelaskan, bahwa Tuhan Yang Maha Esa adalah Allah, tidak lain kecuali Allah. Sebagai saksi sejarah, Prof. Kasman Singodimedjo, menegaskan: “Dan segala tafsiran dari Ketuhanan Yang Maha Esa itu, baik tafsiran menurut historisnya maupun menurut artinya dan pengertiannya sesuai betul dengan tafsiran yang diberikan oleh Islam.” (Lihat, Hidup Itu Berjuang, Kasman Singodimedjo 75 Tahun (Jakarta: Bulan Bintang, 1982), hal. 123-125.)
Lebih jelas lagi adalah keterangan Ki Bagus Hadikusuma, ketua Muhammadiyah, yang akhirnya bersedia menerima penghapusan “tujuh kata” setelah diyakinkan bahwa makna Ketuhanan Yang Maha Esa adalah Tauhid. Dan itu juga dibenarkan oleh Teuku Mohammad Hasan, anggota PPKI yang diminta jasanya oleh Hatta untuk melunakkan hati Ki Bagus. (Siswanto Masruri, Ki Bagus Hadikusuma, (Yogyakarta: Pilar Media, 2005).
Sebenarnya, sebagaimana dituturkan Kasman Singodimedjo, Ki Bagus sangat alot dalam mempertahankan rumusan “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Sebab, rumusan itu dihasilkan dengan susah payah. Dalam sidang-sidang BPUPK, Ki Bagus dan sejumlah tokoh Islam lainnya juga masih menyimpan ketidakpuasan terhadap rumusan itu. Ia, misalnya, setuju agar kata “bagi pemeluk-pemeluknya” dihapuskan. Tapi, karena dalam sidang PPKI tersebut, sampai dua kali dilakukan lobi, dan Soekarno juga menjanjikan, bahwa semua itu masih bersifat sementara. Di dalam sidang MPR berikutnya, umat Islam bisa memperjuangkan kembali masuknya tujuh kata tersebut. Di samping itu, Ki Bagus juga mau menerima rumusan tersebut, dengan catatan, kata Ketuhanan ditambahkan dengan Yang Maha Esa, bukan sekedar “Ketuhanan”, sebagaimana diusulkan Soekarno pada pidato tanggal 1 Juni 1945 di BPUPK. Pengertian inilah yang sebenarnya lebih masuk akal dibandingkan dengan pengertian yang diajukan berbagai kalangan. (Ibid).
Dalam bukunya, “Islam dan Politik, Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin” (1959-1965), (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), Prof. Dr. Ahmad Syafii Maarif juga mencatat, bahwa pada 18 Agustus 1945, Soekarno sebenarnya sangat kewalahan menghadapi Ki Bagus. Akhirnya melalui Hatta yang menggunakan jasa Teuku Mohammad Hasan, Ki Bagus dapat dilunakkan sikapnya, dan setuju mengganti “tujuh kata” dengan “Yang Maha Esa”. Syafii Maarif selanjutnya menulis: “Dengan fakta ini, tidak diragukan lagi bahwa atribut Yang Maha Esa bagi sila Ketuhanan adalah sebagai ganti dari tujuh kata atau delapan perkataan yang dicoret, disamping juga melambangkan ajaran tauhid (monoteisme), pusat seluruh sistem kepercayaan dalam Islam.” Namun tidak berarti bahwa pemeluk agama lain tidak punya kebebasan dalam menafsirkan sila pertama menurut agama mereka masing-masing. (hal. 31).
Tentang makna Ketuhanan Yang Maha Esa identik dengan Tauhid, juga ditegaskan oleh tokoh NU KH Achmad Siddiq. Dalam satu makalahnya yang berjudul “Hubungan Agama dan Pancasila” yang dimuat dalam buku Peranan Agama dalam Pemantapan Ideologi Pancasila, terbitan Badan Litbang Agama, Jakarta 1984/1985, Rais Aam NU, KH Achmad Siddiq, menyatakan:
“Kata “Yang Maha Esa” pada sila pertama (Ketuhanan Yang Maha Esa) merupakan imbangan tujuh kata yang dihapus dari sila pertama menurut rumusan semula. Pergantian ini dapat diterima dengan pengertian bahwa kata “Yang Maha Esa” merupakan penegasan dari sila Ketuhanan, sehingga rumusan “Ketuhanan Yang Maha Esa” itu mencerminkan pengertian tauhid (monoteisme murni) menurut akidah Islamiyah (surat al-Ikhlas). Kalau para pemeluk agama lain dapat menerimanya, maka kita bersyukur dan berdoa.” (Dikutip dari buku Kajian Agama dan Masyarakat, 15 Tahun Badan Penelitian dan Pengembangan Agama 1975-1990, disunting oleh Sudjangi (Jakarta: Balitbang Departemen Agama, 1991-1992).
Jika para tokoh Islam di Indonesia memahami makna sila pertama dengan Tauhid, tentu ada baiknya para politisi Muslim seperti Aburizal Bakrie dan sebagainya berani menegaskan, bahwa tafsir Ketuhanan Yang Maha Esa yang tepat adalah bermakna Tauhid. Itu artinya, di Indonesia, haram hukumnya disebarkan paham-paham yang bertentangan dengan nilai-nilai Tauhid. Tauhid maknanya, men-SATU-kan Allah. Yang SATU itu harus Allah, nama dan sifat-sifat-Nya. Allah dalam makna yang dijelaskan dalam konsepsi Islam, yakni Allah yang satu, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan; bukan Allah seperti dalam konsep kaum Musyrik Arab, atau dalam konsep lainnya.
Kata “Allah” juga muncul di alinea ketiga Pembukaan UUD 1945: “Atas berkat rahmat Allah….”. Sulit dibayangkan, bahwa konsepsi Allah di situ bukan konsep Allah seperti yang dijelaskan dalam al-Quran. Karena itu, tidak salah sama sekali jika para cendekiawan dan politisi Muslim berani menyatakan, bahwa sila pertama Pancasila bermakna Tauhid sebagaimana dalam konsepsi Islam. Rumusan dan penafsiran sila pertama Pancasila jelas tidak bisa dipisahkan dari konteks sejarah munculnya rumusan tersebut.
Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama Nahdlatul Ulama di Situbondo, Jawa Timur, 16 Rabiulawwal 1404 H/21 Desember 1983 memutuskan sebuah “Deklarasi tentang Hubungan Pancasila dengan Islam”, yang antara lain menegaskan: (1) Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara Republik Indonesia bukanlah agama, tidak dapat menggantikan agama dan tidak dapat dipergunakan untuk menggantikan kedudukan agama. (2) Sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagai dasar Negara Republik Indonesia menurut pasal 29 ayat 1 Undang-undang Dasar (UUD) 1945, yang menjiwai sila yang lain, mencerminkan tauhid menurut pengertian keimanan dalam Islam. (3) Bagi Nahdlatul Ulama (NU) Islam adalah akidah dan syariah, meliputi aspek hubungan manusia dengan Allah dan hubungan antarmanusia. (4) Penerimaan dan pengamalan Pancasila merupakan perwujudan dan upaya umat Islam Indonesia untuk menjalankan syariat agamanya. (5) Sebagai konsekuensi dari sikap di atas, NU berkewajiban mengamankan pengertian yang benar tentang Pancasila dan pengamalannya yang murni dan konsekuen oleh semua pihak. (Lihat, pengantar K.H. A. Mustofa Bisri berjudul “Pancasila Kembali” untuk buku As’ad Said Ali, Negara Pancasila, Jalan Kemaslahatan Berbangsa, (Jakarta: LP3ES, 2009).
Kaum Muslim perlu mencermati kemungkinan adanya upaya sebagian kalangan untuk menjadikan Pancasila sebagai alat penindas hak konsotistusional umat Islam, sehingga setiap upaya penerapan ajaran Islam di bumi Indonesia dianggap sebagai usaha untuk menghancurkan NKRI. Dalam ceramahnya saat Peringatan Nuzulul Quran, Mei 1954, Natsir sudah mengingatkan agar tidak terburu-buru memberikan vonis kepada umat Islam, seolah-olah umat Islam akan menghapuskan Pancasila. Atau seolah-olah umat Islam tidak setia pada Proklamasi. ”Yang demikian itu sudah berada dalam lapangan agitasi yang sama sekali tidak beralasan logika dan kejujuran lagi,” kata Natsir. Lebih jauh Natsir menyampaikan, ”Setia kepada Proklamasi itu bukan berarti bahwa harus menindas dan menahan perkembangan dan terciptanya cita-cita dan kaidah Islam dalam kehidupan bangsa dan negara kita”
Natsir juga meminta agar Pancasila dalam perjalannya tidak diisi dengan ajaran-ajaran yang menentang al-Quran, wahyu Ilahi yang semenjak berabad-abad telah menjadi darah daging bagi sebagian terbesar bangsa Indonesia. (M. Natsir, Capita Selecta 2).
Contoh penyimpangan penafsiran Pancasila pernah dilakukan dengan proyek indoktrinasi melalui Program P-4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila). Pancasila bukan hanya dijadikan sebagai dasar Negara. Tetapi, lebih dari itu, Pancasila dijadikan landasan moral yang seharusnya menjadi wilayah agama. Penempatan Pancasila semacam ini sudah berlebihan. Di Majalah Panji Masyarakat edisi 328/1981, mantan anggota DPR dari PPP, Ridwan Saidi pernah menulis kolom berjudul ”Gejala Perongrongan Agama”. Sejarawan dan budayawan Betawi ini mengupas dengan tajam pemikiran Prof. Dardji Darmodiharjo, salah satu konseptor P-4.
”Saya memandang sosok tubuhnya pertama kali adalah pada kwartal terakhir tahun 1977 pada Sidang Paripurna Badan Pekerja MPR, waktu itu Prof. Dardji menyampaikan pidato pemandangan umumnya mewakili Fraksi Utusan Daerah. Pidatonya menguraikan tentang falsafah Pancasila. Sudah barang tentu uraiannya itu bertitik tolak dari pandangan diri pribadinya belaka. Dan sempat pula pada kesempatan itu Prof. Dardji menyampaikan kejengkelannya ketika katanya pada suatu kesempatan dia selesai ceramah tentang sikap hidup Pancasila, seorang hadirin bertanya padanya bagaimana cara gosok gigi Pancasila.”
Kuatnya pengaruh Islamic worldview dalam penyusunan Pembukaan UUD 1945 – termasuk Pancasila – terlihat jelas dalam sila kedua: Kemanusiaan yang adil dan beradab. Manusia Indonesia harus bersikap adil dan beradab. Adil dan adab merupakan dua kosa kata pokok dalam Islam yang memiliki makna penting. Salah satu makna adab adalah pengakuan terhadap Allah sebagai satu-satunya Tuhan dan Muhammad shalallahu ‘alaihi wasallam sebagai Nabi, utusan Allah. Menserikatkan Allah dengan makhluk – dalam pandangan Muslim – bukanlah tindakan yang beradab.
Meletakkan manusia biasa lebih tinggi kedudukannya dibandingkan utusan Allah Subhaanahu wa ta’ala tentu juga tidak beradab. Menempatkan pezina dan penjahat lebih tinggi kedudukannya dibandingkan dengan orang yang bertaqwa, jelas sangat tidak beradab.
Jadi, jika Golkar atau siapa pun bersungguh-sungguh menegakkan Pancasila di Indonesia, siapkah Golkar menegakkan Tauhid dan adab di bumi Indonesia? Wallahu a’lam bil-sahawab.*
Paparan lebih lengkap tentang Pancasila bisa dilihat dalam buku: Adian Husaini, “Pancasila bukan untuk Menindas Hak Konstitusional Umat Islam” (Jakarta: GIP, 2010).
Catatan Akhir Pekan [CAP] Adian Husaini bekerjasama dengan Radio Dakta 107 FM